Pemilu; berbicara soal pemilu,
pastilah berbicara soal pilihan. Pemilu, adalah sebuah proses pemilihan
seseorang untuk jabatan politik tertentu. Dan dalam proses pemilihan tersebut,
seorang pemilih tentu dipengaruhi beberapa faktor, sehingga membuat si pemilih
merasa perlu untuk turut menyumbangkan suara. Aurel Croissant, seorang profesor
ilmu politik dari University of Heidelberg, mengatakan ada tiga faktor
pendorong yang mempengaruhi seorang pemilih untuk terlibat dalam proses pemilu:
fungsi keterwakilan, integrasi, serta kemampuan dan jaminan stabilitas
seseorang untuk menjalankan jabatannya. Lalu pertanyaannya adalah: bagaimana
jika faktor tersebut tak sanggup dipenuhi oleh sang calon empunya jabatan?
Kebanyakan pemilih di Indonesia,
tak mempermasalahkan apabila seorang calon tidak memlih faktor pendorong kedua
dan ketiga. Dalam The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century, dijelaskan bahwa masyarakat khususnya di skala lokal, masih
melihat faktor keterwakilan; entah ditinjau dari aspek geografis, maupun ikatan
emosional, sebagai salah satu faktor kuat yang membuat mereka
turut menyumbang suara. Wajar, karena isu yang dijual oleh para bakal
calon ini cenderung lebih dekat dengan kepentingan pemilih lokal. Akan tetapi
seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan kualitas pemilihan. Berbekal
pendidikan politik yang baik, hal-hal yang dinilai tidak relevan dengan jaminan
mutu, kini tidak lagi menjadi jaminan faktor pendorong. Integrasi dan kemampuan
seseorang untuk menjalankan jabatan, kini dipandang sebagai faktor utama yang
dapat mempengaruhi perolehan suara. Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa
tidak semua bakal calon yang terlibat dalam proses pemilu, memiliki jaminan
mutu tersebut. Dalam sebuah sistem kepemimpinan yang menjunjung tinggi asas
demokrasi, setiap individu dinilai memiliki kesempatan yang sama untuk
menduduki sebuah jabatan politik. Asalkan sanggup memenuhi syarat dan ketentuan
yang berlaku, baik/buruk-nya jejak rekam sang bakal calon, tentu menjadi
pertimbangan nomor sekian.
Berangkat dari kecemasan inilah,
muncul gerakan masif yang mulai merambat dari skala lokal menuju ke skala
nasional. Gerakan ini disebut sebagai gerakan golongan putih atau biasa disebut
golput. Tidak memilih, adalah antitesa dari hiruk pikuk pemilu. Namun sekalipun
begitu, golput bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam proses pemilu, karena
pemilu di Indonesia, termasuk pilkada menggunakan sistem legitimasi
formal, dan prinsip memilih sebagai sebuah voluntary voting. Sebagaimanapun
tingginya angka golput, tidak akan pernah membatalkan hasil pemilu. Meski
secara substansif, tingginya angkat golput ini merepresentasikan rendahnya
legitimasi serta kepercayaan para pemilih terhadap bakal calon, atau bahkan
pemilu itu sendiri. Namun jika ingin dicermati, gerakan golput sebenarnya
memiliki kecenderungan membela hak pilih, hanya saja hak pilihnya bukan untuk
memilih partai, tapi hak pilih untuk tidak memilih.
“If voting changed anything, they’d make it illegal,” Emma Goldman
Beberapa bulan belakangan ini terjadi sebuah fenomena yang
cukup menggetirkan: kampanye hitam terhadap golput). Di berbagai forum
dan media, baik media sosial maupun konvensional, terjadi sebuah penggiringan
opini bahwa orang-orang golput adalah sekumpulan pemalas yang tidak mau memakai
hak politiknya sehingga membuat demokrasi di Indonesia tidak meningkat
kualitasnya dan pada akhirnya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat tidak
meningkat.
Ini
adalah sebuah fenomena yang menggelikan karena seakan-akan semua permasalahan
yang ada di bangsa ini adalah kesalahan golput padahal tidak ada teori ilmu
politik manapun atau fakta sejarah yang menunjukkan bahwa golput memiliki
hubungan dengan kualitas demokrasi maupun kehidupan dan kesejahteraan
masyarakat.
Golput
pada hakekatnya juga sebuah hak politik yang dipergunakan yaitu hak untuk tidak
memilih karena berbagai alasan. Terlalu kerdil dan dangkal rasanya untuk
menyatakan golput adalah sebuah tindakan yang salah dari para pemalas. Ada
berbagai pertimbangan dan alasan rasional di balik keputusan untuk menjadi
golput di masa seperti sekarang.
Saya sendiri adalah seorang golput sejati. Saya tidak pernah
menggunakan hak pilih saya dalam 5 Pilkada belakangan ini untuk suatu calon
tertentu sejak 2012, tahun di mana umur saya dinyatakan cukup oleh negara untuk
berpartisipasi dalam pemilu, dan mungkin juga saya tidak akan menggunakan hak
pilih saya untuk suatu partai atau calon di masa depan.
Pada pemilu 1999, sistem pemilihan presiden yang digunakan
adalah tidak langsung. Pada waktu itu euforia terjungkalnya Orba begitu besar
dan memberikan keuntungan besar bagi PDI-P, partai yang waktu itu ketua umumnya
Megawati Soekarnoputri dianggap publik sebagai korban kezaliman Soeharto. Harapan kita
akan suatu perubahan yang lebih baik cukup besar pada waktu itu, akan tetapi
seiring berjalannya waktu, mulai terlihat bahwa yang namanya “perubahan” tidak
bisa diharapkan dari segerombolan serigala di pemerintahan. Serigala-serigala
yang ironisnya dulu berjuang menumbangkan tiran bernama Soeharto kini menjadi
pemangsa-pemangsa baru.
Gus Dur digantikan oleh wakilnya, Megawati. Masa pemerintahan
Megawati bisa dianggap sebagai salah satu masa paling korup dalam waktu yang
sangat singkat. Skandal-skandal korupsi pemerintahan ini baru mulai terkuak di
pemerintahan berikutnya dan cukup bisa menggambarkan betapa mengerikannya
keserakahan para perwakilan partai “wong cilik” ini dalam menghabisi uang
rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Prestasi “puncak” pemerintahan ini
adalah pembunuhan aktivis HAM Munir yang sampai saat ini masih diselimuti
misteri. Sejak
saat itu saya tidak akan pernah lagi percaya terhadap Golkar maupun PDI-P yang
terlalu munafik dalam berkuasa maupun ber-oposisi. Saya pun mulai berpikir jika
PKI saja yang sampai HARI INI tidak terbukti melakukan tindak vandalisme seperti
yang dituduhkan pada tragedi 65 bisa dibubarkan, kenapa kedua partai yang silih
berganti berkuasa dan menghamburkan uang rakyat selama 4 dekade masih bisa
eksis sampai hari ini?
Pada saatnya pemilu 2004, kekecewaan dan pesimisme kita
terhadap pemerintah semakin menjadi-jadi. Di pemilu kali ini, pemilihan
presiden dilakukan secara langsung dan pada waktu itu muncul figur bernama
Susilo Bambang Yudhoyono. Figur ini adalah salah satu menteri paling dipercaya
oleh Megawati pada awalnya. Akan tetapi ketika ambisi politik Yudhoyono makin
terlihat, hubungannya dengan Megawati semakin meruncing dan pada akhirnya yang
bersangkutan terpaksa mengundurkan diri dari kabinet. Yudhoyono saat itu
berpasangan dengan putra daerah Sulsel dan senior kita di HmI yang kebetulan
saat itu juga merupakan salah satu menteri, yaitu Jusuf Kalla. Jika kita mau
objektif, kapabilitas JK tidak usah diragukan lagi, tetapi ada satu kekurangan
beliau, yaitu; Nepotisme. Nepotisme JK meliputi banyak hal, diantaranya mengenai empowerment dan distribusi kekuasaannya. Kadang
kita bertanya-tanya sendiri, kenapa orang-orang Sulsel bisa merajai politik
Indonesia? Dari para koruptor sampai yg nangkap koruptor.
Publik pada waktu itu melihat Yudhoyono sebagai figur yang
dizalimi, sama seperti persepsi terhadap Megawati ketika reformasi di 1998. Dua
individu yang berbeda tapi menggunakan topeng penarik simpati yang sama dan
siapapun yang memakai topeng untuk menarik simpati tidak layak untuk dipercaya.
Pemerintahan Yudhoyono pada 2004-2009 terbukti kembali
meninggalkan banyak kekecewaan. Korupsi tetap merajalela, salah satu pelakunya
malahan besan presiden sendiri. Janji Yudhoyono untuk menyelesaikan kasus Munir
dan pelanggaran HAM 98 juga tidak terwujud dan tentunya siapa yang bisa
menghapus tragedi pembiaran meluapnya Lumpur Lapindo dari sejarah sebagai salah
satu “tinta emas” pemerintahan Yudhoyono yang pertama?
Pemerintahan Yudhoyono pertama juga menunjukkan bagaimana
sekumpulan orang pintar di tingkat eksekutif pada akhirnya cuma handal menyusun
konsep tapi payah dalam melakukan eksekusi. Rencana-rencana pembangunan
infrastruktur, pembukaan akses finansial, diversifikasi energi dan lain-lain
pada akhirnya hanya menjadi wacana di atas kertas saja.
Warisan “jago menyusun wacana” dari pemerintahan Yudhoyono
pertama ternyata telah berhasil menulari capres-capres yang lain. Ini sangat
terlihat dalam debat-debat capres. Di dalam debat-debat tersebut, semua capres
menyampaikan wacana dan janji-janji yang sama tanpa adanya elaborasi yang lebih
jelas untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka memang memiliki kapasitas untuk
memimpin salah satu perekonomian dan demokrasi terbesar di dunia.
Sebagai contoh; ketika isu mengenai kemandirian energi
diangkat, semua capres berjanji bahwa mereka tidak akan menaikkan harga BBM
demi kesejahteraan masyarakat. Tapi tidak ada satupun yang mengelaborasi dengan
cukup jelas tentang apa rencana mereka tentang energi terbarukan, apa yang akan
mereka lakukan untuk mengurangi impor BBM, dan lain-lain.
Semua capres bertingkah layaknya anak-anak remaja akil balik
berlingkar otak mini dan kebingungan sehingga mereka mencoba segala cara untuk
memberikan jawaban yang terdengar enak di kuping tapi kosong secara
substansi.
Melihat fakta-fakta di atas, apakah golput bisa disalahkan atas
lahirnya pemerintahan yang buruk atau sebaliknya, pemerintahan yang buruklah
yang menjadi penyebab utama semakin pesimisnya masyarakat terhadap pemilu dan
meningkatnya golput?
Menjelang pemilu 2014, seperti saya katakan di atas, mulai
muncul fenomena yang bertujuan menggiring masyarakat ke bilik pemilihan untuk
memilih partai dan presiden. Selain kampanye hitam terhadap golput, juga muncul
jargon-jargon untuk menjustifikasi kenapa kita “harus” memilih.
Salah satu justifikasi yang paling sering digaungkan adalah
“memang tidak ada yang sempurna karena itu pilihlah yang terbaik dari yang
terburuk” atau bahasa kerennya adalah “the lesser of all evils”.
Menurut pendapat saya, justifikasi seperti itu adalah sesuatu
yang ngawur. The lesser of all evils is still an evil. Jika calon A punya track
record pernah korupsi 100 M, calon B 200 M dan calon C 300 M, tetap saja
memilih calon A adalah memilih seorang koruptor untuk menjadi pemimpin. Dan
begitu dia menjadi pemimpin, hampir bisa dipastikan korupsinya lebih gila dari
calon B dan calon C digabung.
Jadi apa harus ada pemimpin yang benar-benar bersih? Ya
memang. Hanya orang bodoh yang mau dirinya dipimpin oleh bandit dan memilihnya
secara sadar.
Dan sekarang pertanyaannya; kenapa tidak pernah muncul
pemimpin bersih yang benar-benar layak dipilih selama ini? Jawabannya bukan di
masalah memilih atau tidak, jawabannya ada di dalam masyarakat itu sendiri.
Masyarakat yang brengsek hanya akan melahirkan
pemimpin-pemimpin yang brengsek. Masyarakat yang munafik akan melahirkan
pemimpin-pemimpin yang munafik. Masyarakat yang bermental bandit akan
mendudukkan gembong-gembong bandit pada tampuk-tampuk kekuasaan.
Sekarang coba lihat masyarakat Indonesia secara keseluruhan
dan nilai sendiri. Lupakan jargon-jargon nasionalisme semu seperti “bangsa
Indonesia adalah bangsa yang besar” dan lain-lain sebab pada kenyataannya
masyarakat kita pada saat ini benar-benar sampah.
Di saat bangsa lain sudah mulai membentuk masyarakat madani
yang mandiri tanpa harus bergantung pada pemerintah, masyarakat kita, ironisnya
di sebagian besar anak mudanya, masih bermental inlander atau budak yang
mengharapkan keselamatan dan perubahan dari figur seorang ratu adil atau satria
piningit.
Mental instant juga masih terpatri dalam masyarakat kita dan
ini terlihat dari banyaknya buku-buku sampah tentang cara cepat menjadi kaya di
deretan best seller di samping tentunya buku-buku so called “selebtweet”.
Sistem pendidikan kita yang hanya berbasis nilai bukan proses juga menumbuhkan
mental korup sejak usia dini. Bagaimana mungkin ada pemimpin bersih atau
peningkatan kualita kehidupan bisa muncul dari masyarakat sampah seperti ini?
Pada akhirnya yang harus disadari adalah peningkatan
kehidupan dan kesejahteraan suatu masyarakat harus dimulai dari
individu-individu di dalam masyarakat itu sendiri, bukan pada figur seorang
pemimpin. Selama masih banyak individu yang bermental budak, oportunis maupun
manja, maka kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. Yang menyedihkan adalah
individu-individu semacam ini justru semakin menjamur di segmen kelas menengah
dan muda, segmen berpendidikan yang diharapkan bisa menjadi penggerak.
Anda boleh memiliki gadget bernilai jutaan dan berkantor di
gedung menterang, akan tetapi selama anda masih dengan noraknya mengharapkan
perubahan akan datang dari seorang figur yang anda buzz di social media dan
bela habis-habisan seakan dia adalah Tuhan agar banyak pemilih yang memilih
dia, maka anda tetap saja bermental seorang budak; seorang pandir yang tidak
memiliki kepercayaan diri yang cukup bahwa perubahan kehidupannya ada di
tangannya sendiri.
Kaum golput bukanlah sekumpulan pemalas penyebar pesimisme
seperti yang banyak didengung-dengungkan akhir-akhir ini. Sebaliknya, kaum
golput adalah orang-orang optimis yang merasa tidak perlu memberikan mandat
atas kehidupannya kepada figur-figur bandit. Kaum golput adalah orang-orang
mandiri yang merasa tidak perlu menghamba dengan putus asa dan berdoa akan
kehadiran sosok ratu adil atau satria piningit. Kami bukan budak dan kami bukan
penjilat kekuasaan.
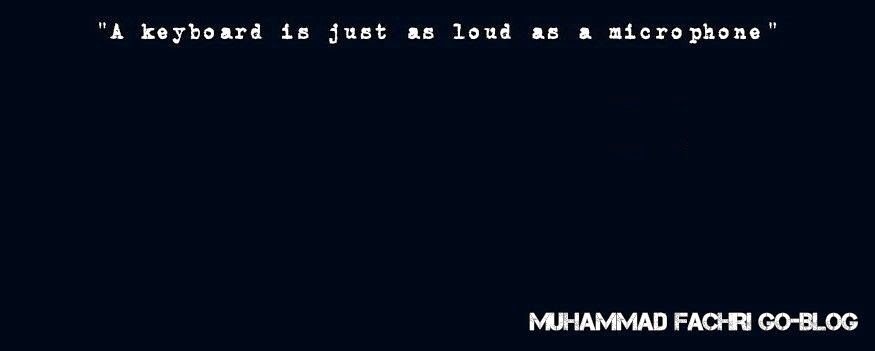



No comments:
Post a Comment